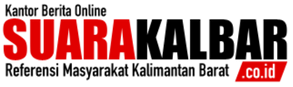Suara Kalbar – Perkembangan industri perkebunan sawit di wilayah Boven Digul, Papua Selatan, tengah menjadi sumber pertentangan dengan masyarakat adat Suku Awyu. Mereka sedang menggugat izin perkebunan yang merambah hingga mencapai tanah adat mereka. Di sisi lain, pemerintah justru mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan sawit di Papua Barat.
Penolakan masyarakat adat Suku Awyu terhadap izin pembukaan perkebunan sawit saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Pada tahun 2021, pemerintah daerah setempat memberikan izin untuk membuka perkebunan seluas lebih dari 36 ribu hektare di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga berencana mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 90 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
Namun, Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Papua Selatan (Ampera PS) dengan tegas menolak rencana ini. Titin Betaubun, Presiden Mahasiswa Universitas Musamus, Merauke, menyebut bahwa penolakan ini didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat adat sangat bergantung pada hutan yang menjadi rumah mereka. Bagi mereka, hutan bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga identitas dan spiritualitas yang tak ternilai harganya.
“Siapa pun dari kita, ketika rumah kita mau dirampok oleh orang lain, kita pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk menjaga agar rumah kita tetap aman. Itu pun yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat Suku Awyu,” ujarnya dalam pernyataan bersama.
Mahasiswa, kata Titin, saat ini sedang besama-sama berjuang mempertahankan tanah adat dan rumah Suku Awyu.
“Kami menolak dengan tegas deforestasi yang secara masif terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan terus berupaya untuk memanipulasi masyarakat, untuk menerima perusahaan yang mereka miliki,” tambah Titin.
Upaya apa pun yang berarti menjadi jalan untuk deforestasi hutan adat akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dampak itu akan merembet, tidak hanya ke sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dukungan juga disampaikan Koordinator Ampera PS, Norbertus Abagaimu.
“Kami sebagai aliansi memberikan dukungan moril kepada orang tua dan anak-anak muda hari ini yang merasa resah dengan adanya beberapa korporasi yang melegalkan tindakan-tindakannya secara tidak humanis,” ujarnya.
Ampera PS meminta pemerintah daerah Papua Selatan dan PTUN Jayapura bisa bersikap netral dan turut menyuarakan hak-hak masyarakat adat.
“Karena kami tahu, bahwa ke depan alam semakin berubah karena adanya deforestasi besar-besaran, khususnya di Papua Selatan,” ujarnya lagi.
Abagaimu juga mengingatkan bahwa perjuangan masyarakat adat Awyu penting bagi kehidupan seluruh masyarakat.
“Hutan yang mereka pertahankan penting untuk keberlangsungan hidup kita. Mereka melindungi hutan mereka dari ancaman deforestasi yang sering sekali disebabkan oleh proyek-proyek ekstraktif negara dan pelaku ekonomi lainnya di Papua atau di wilayah lainnya,” tegas dia.
Apa yang terjadi pada masyarakat adat Marind nampaknya menjadi pelajaran berharga. Tokoh adat Marind, Elisabeth Ndiwaen, mengatakan mereka telah kehilangan hutan adat karena datangnya investasi.
“Saya punya perjuangan ini sudah dari 2009 sampai 2023 ini. Yang saya mau imbaukan untuk semua pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah, untuk melihat masalah-masalah yang sudah terjadi di atas tanah, hutan, yang sekarang sudah rusak,” ujarnya.
Karena itu lah, ketika perusahaan perkebunan akan masuk ke wilayah adat Awyu, bukan tidak mungkin kerusakan yang sama akan terjadi.
“Kami punya kehidupan masyarakat di atas tanah dan hutan adat yang sudah digusur oleh perusahaan. Itu pemerintah tidak bisa tinggal diam, harus melihat. Apalagi yang sekarang saya punya saudara-saudara dari Suku Awyu, kami ini senasib,” ujarnya.
Ndiwaen menyebut mereka berjuang menegakkan keadilan di atas tanah leluhur. Kerusakan yang terjadi di tanah Suku Marind, seharusnya bisa dicegah untuk terjadi pada Suku Awyu.
Dia menambahkan, “Selama ini kami punya hutan, tanah sudah habis digusur. Tapi kami punya kehidupan sampai detik ini kami hidup di dalam penderitaan dan kesengsaraan.”
Gugatan Dua Lembaga
Gugatan intervensi di PTUN Jayapura dilayangkan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Keduanya memiliki kepentingan di pengadilan untuk membela hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua. Pusaka dan Walhi meyakini pemberian izin kepada perusahaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan mengkonversi kawasan hutan Papua dalam skala luas, melanggar hak masyarakat adat dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Tigor Hutapea, staf advokasi Yayasan Pusaka dalam pernyataannya memaparkan wilayah yang ditetapkan menjadi konsesi perusahaan sawit merupakan ekosistem hutan adat Awyu Woro.
“Keberadaan hutan ini menjadi sumber air bersih bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di dua belas kampung. Hutan dan aliran sungai juga menjadi ruang produksi untuk berburu dan memancing ikan, menangkap buaya, dan meramu sumber pangan,” ujarnya.
Secara filosofis, masyarakat adat Papua memandang tanah dan sumber daya alam di dalamnya memiliki kedudukan dan posisi yang penting dan mempengaruhi gerak hidup masyarakat. Tanah diyakini sebagai harapan bersama, dan tanah sebagai relasi iman. Tanah sebagai harapan bersama bermakna tanah adalah harta abadi dan terakhir. Sementara konsep tanah sebagai harapan hidup berkaitan erat dengan harapan hidup masyarakat asli Papua, di mana mereka tidak bisa hidup tanpa tanah.
“Masyarakat adat hidup, bekerja dan tinggal di atas tanah. Tanah menciptakan dan melahirkan orang asli Papua sebagai manusia sejati. Oleh karenanya, tanah juga dianggap sebagai Mama sejati, karena masyarakat adat hidup dan dibesarkan oleh tanah milik mereka,” tambah Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional.
Karena itu lah, Pusaka dan Walhi menandaskan pengambilan wilayah adat secara sepihak sama artinya mengambil seluruh kehidupan masyarakat.
Ekspansi di Manokwari
Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sisi lain pada Sabtu (15/7) di Manokwari, Papua Barat, justru mendorong ekspansi budidaya sawit. Dia meminta pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit secepatkan di kawasan itu. Alasannya, petani sawit Papua Barat selama ini harus menjual sawit hingga ke luar daerah.
“Jadi, yang selama ini harus menjual sawitnya bahkan sampai ke Makassar, sekarang masyarakat akan menjual di provinsi sendiri. Saya perintahkan supaya dipercepat,” kata Amin soal pendirian pabrik itu.
Petani sawit di Manokwari dan sekitarnya harus mengirim panen mereka ke wilayah lain, dan memakan waktu. Kondisi ini menurunkan kualitas sawit mereka dan menekan harga beli. Mendirikan pabrik di Papua dinilai memecahkan persoalan itu. Pendirian pabrik dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp80 miliar dan tambahan dari sumber dana pinjaman lain.
Data menyebutkan kebun kelapa sawit terpusat di tiga distri,k yaitu Prafi, Warmare dan Masni. Ada sekitar 5.000 kepala keluarga yang mengelola kebun dengan total luas 9.400 hektare atau rata-rata setiap kepala keluarga memiliki kebun sawit seluas 1,88 hektare. Sebagian sawit itu telah berumur tua dan tidak cukup produktif, dan kerena itu Amin juga datang ke Manokwari untuk memberikan bantuan dalam skema Peremajaan Sawit Rakyar (PSR).
“Sawit di daerah ini, 9.000 hektare ini sudah mulai tidak produktif karena sudah tua, kemudian sudah dimulai adanya PSR, peremajaan sawit sejak 2021. Ini suatu perubahan supaya bisa produktif lagi dan hasilnya supaya besar lagi,” kata Wapres.
Bumi Cendrawasih memiliki luasan tutupan hutan 33,8 juta hektare. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), hingga 2021 luas lahan sawit milik perusahaan di pulau itu mencapai 214 ribu hektare lebih. Organisasi ini juga mengklaim, sektor sawit mampu menyerap 43.000 tenaga kerja di seluruh wilayah Papua.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS