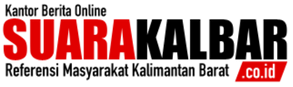Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.
SECARA etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin corruptio yang merupakan kata kerja corrumpere yang memiliki makna busuk, rusak, kotor, menggoyahkan, dan memutarbalik. Dalam arti yang literal, segala perbuatan yang berafiliasi dengan karakter dan sifat tersebut digolongkan sebagai korupsi.
Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku Penegakan Hukum Progresif (2010) membedakan korupsi dalam dua arti. Pertama, korupsi non-konvensional. Korupsi non-konvensional bukanlah korupsi dalam arti yuridis-formal (tindak pidana korupsi) melainkan perbuatan-perbuatan yang bersifat kriminogen untuk melahirkan korupsi konvensional. Misalnya ketidakjujuran dan hedonisme. Bisa dikatakan, korupsi non-konvensional merupakan bibit-bibit dari pada lahirnya korupsi konvensional di kemudian hari.
Kedua, korupsi konvensional. Korupsi konvensional merupakan korupsi dalam arti yuridis-formal sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan positif. Korupsi konvensional meliputi perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.
Gratifikasi sendiri menjadi salah satu dari 7 jenis dari tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Oleh karena itu, gratifikasi pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, gratifikasi positif. Merupakan gratifikasi dalam arti yang umum dan tidak diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berlawanan dengan tugas dan jabatannya. Contoh: memberikan parsel lebaran kepada tetangga yang kurang mampu.
Kedua, gratifikasi negatif. Merupakan gratifikasi dalam arti yang spesifik dan diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berlawanan dengan tugas dan jabatannya. Contoh: seorang pengusaha yang memberikan parsel lebaran dan uang hari raya kepada bupati selaku pemangku kebijakan publik daerah setempat.
Menurut Pasal 12B ayat (1) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Setiap perbuatan yang melanggar Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milliar. Inilah yang disebut sebagai gratifikasi negatif.
Akan tetapi, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak ia menerima gratifikasi. Selanjutnya, KPK akan menilai apakah gratifikasi tersebut termasuk pemberian suap atau tidak. Jika tidak, gratifikasi akan dikembalikan kepada pelapor.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi (dalam arti negatif/tindak pidana) merupakan pemberian yang dapat dinilai secara ekonomis, dapat disita oleh KPK (jika terbukti gratifikasi negatif), dan dapat dinilai secara fisik. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana jika gratifikasi yang diberikan adalah gratifikasi seks? Secara eksplisit, tidak ada ketentuan yuridis yang mengkualifikasi layanan seks sebagai jenis gratifikasi.
Apakah gratifikasi seks dapat dimasukkan dalam konteks fasilitas lainnya sebagai tertuang dalam penjelasan Pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001. Menurut penulis, layanan seks tidak bisa dimasukkan dalam kualifikasi fasilitas lainnya. Alasannya, seks sulit dinilai secara ekonomis dan tidak dapat disita/diperiksa oleh KPK. Misalnya terkait aturan penerima gratifikasi yang tidak bisa dijerat pidana jika melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak ia menerima gratifikasi, teknisnya kemudian penerima gratifikasi akan menyerahkan barang/bukti jasa kepada KPK untuk diperiksa dan dinilai. Lalu, jika gratifikasi berbentuk seks bagaimana teknis penyerahannya kepada KPK?
Secara faktual, gratifikasi seks memang potensif dijadikan modus operandi untuk melakukan praktik gratifikasi. Oleh sebab itu, langkah yuridisnya adalah dengan menetapkan layanan seks sebagai bagian dan kualifikasi gratifikasi beserta teknis penetapannya. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentunya menjadi solusi praktis.
*Penulis Adalah Pegiat Hukum Indonesia