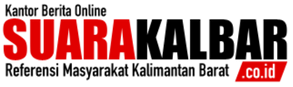|
| Ilustrasi – Omnibus Law [Foto: Pikiran Rakyat] |
Oleh: Fanti Setiawati*
PENGESAHAN UU Ciptaker Omnibus Law oleh parlemen beberapa waktu
lalu benar-benr mengundang dharar (bahaya).
UU sapu jagat ini tidak hanya mengancam nasib buruh hingga memancing aksi
protes dari bbagai kalangan. Tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan.
Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) melalui Sekjend-nya Dewi Kartika, menyoroti tambahan kategori
kepentingan umum untuk pengadaan tanah dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sorotan Dewi ini terkait dengan Pasal
121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal ini menambah empat poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan
gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan
lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
BUMN dan BUMD. Kawasan lain yang belum diatur RUU Cipta Kerja akan ditetapkan
dengan peraturan presiden (PP). (Kompas.com,
12/8/2020)
Dalam pernyataa
tersebut, Dewi menilai ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi
lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi
lahan yang dipermudah akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan
lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Menurutnya, argumentasi
penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan para
investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan
infrastruktur serta kegiatan bisnis. Definisi kepentingan umum diperluas dengan
menambahkan kepentingan investor pertambangan, pariwisata, industri dan kawasan
ekonomi khusus (KEK) ke dalam kategori kepentingan umum.
Dari data (KPA), terdapat 659 konflik
agraria yang terjadi pada 2017. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh
kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan
politik. Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu
sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan
timbul pada komoditas kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya praktik
pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak
masyarakat atas tanah. (Katadata,
6/10/2020)
Berdasarkan Catatan Walhi, saat
kebakaran hutan dan lahan hebat melanda Indonesia tahun 2015, ada 349
perusahaan terlibat. Dengan penghapusan pasal 88 UU 32 Tahun 2009, pemerintah
tak bisa memberi sanksi pidana bagi korporasi. Artinya, peran negara melemah
terhadap pelanggaran izin atau kerusakan lingkungan. (Mongabay, 18/3/2020)
Indonesian Centre for
Environmental Law (ICEL) dan Walhi sendiri sejak awal memberikan catatan kritis
terhadap draf UU ini. Reynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL mengatakan,
terdapat beberapa bidang isu penting di sini antara lain lingkungan hidup, penataan
ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan,
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan dan
keanekaragaman hayati. (Mongabay.co.id)
Semua fakta ini menunjukkan bahwa
sebelum pengesahan UU Ciptaker Omnibus Law, praktik pelaksanaan UU Pertanahan
telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran. Tentu rakyat kecillah yang
menjadi korban utamanya.
Dilansir dari MuslimahNews.com,
setidaknya ada beberapa poin yang bermasalah dalam pasal-pasal di UU Omnibus
Law Cipta Kerja. Pertama, pemberian
izin lingkungan dan Amdal yang terdapat dalam pasal 24 UU Ciptaker. Jika
sebelumnya Amdal menjadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan menjadi
syarat izin usaha, maka dalam UU Omnibus Law aturan itu disederhanakan. Izin
lingkungan menjadi bagian dari izin usaha. Amdal bukan lagi prasyarat perizinan
namun sebatas sebagai faktor yang dipertimbangkan.
Selain itu, pemberian izin lingkungan
kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi
memberikan rekomendasi izin apapun. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan,
dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Namun, dalam UU Cipta Kerja,
Komisi Penilai Amdal (KPA) dihapus. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan
masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Uji kelayakan Amdal justru dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli
bersertifikat. Aturan ini memberi peluang bagi swasta sebagai pengganti KPA.
Jika ini terjadi, kongkalikong antara pengusaha dan swasta sangat terbuka
lebar. Uji kelayakan Amdal bisa saja dimanipulasi demi terbitnya perizinan
usaha.
Kedua,
hilangnya partisipasi masyarakat. Dalam UU Cipta kerja, penyempitan peran
masyarakat dalam perumusan Amdal juga terjadi. Berdasarkan UU Cipta Kerja
masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang
terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. UU ini juga
semakin mempersempit akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini terlihat dari
dibatasinya cara untuk mengakses keputusan kelayakan lingkungan hidup serta
mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut.
Masyarakat tak dapat lagi mengajukan keberatan
Amdal dalam aturan baru tersebut. Hal ini berpotensi membungkam suara publik
bila mereka mengeluhkan kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
dan habitat tempat mereka hidup.
Ketiga,
pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal 37 UU Ciptaker disebutkan,
“Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.” Pasal ini mengubah ketentuan
pasal 49 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan ini mengubah
kewajiban bertanggungjawab terjadinya kebakaran hutan di area kerja menjadi
hanya wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
Wajar jika UU ini menyulut protes dari
berbagai pihak. Sebab sangat nyata UU ini tidak berpihak kepada rakyat. Kemaslahatan
rakyat yang ingin diwujudkan melalui pengesahan UU Omnibus Law ini hanyalah
dalih. Faktanya, penguasaan lahan dalam skala besar tercatat dimiliki oleh para
pemodal.
Pemerintah mengklaim bahwa masyarakat yang
mengembangkan usaha perkebunan di lokasi yang masuk dalam kawasan hutan namun
mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha dan pemanfaatan lahan, melalui UU
Omnibus Law ini dapat memiliki kepastian lahan tanpa terhambat aspek
administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi.
Namun klaim pemerintah ini kontradiksi dengan data KPA yang
menyatakan bahwa 46% lahan di luar kawasan hutan dikuasai oleh perusahaan
perkebunan. Luasnya adalah 33,5 juta hektare, dikuasai lewat hak guna usaha
(HGU). Adapun di kawasan hutan, 35 juta hektare dikuasai hutan tanaman
industri, lewat hak pengusahaan hutan (HPH), dan perusahaan konservasi.
Tahun 2017, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga
pernah menyatakan bahwa dari seluruh wilayah daratan Indonesia, 71% dikuasai
oleh korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan skala besar, dan 7%
oleh para konglomerat. Sedangkan rakyat kecil cuma menguasai sisanya. (Mongabay.co.id)
Jadi, rakyat mana yang dijamin UU Omnibus Law ini? Berbagai
penderitaan yang dialami rakyat saja sudah cukup menyulitkan rakyat untuk
memiliki lahan, apalagi mengelola kawasan lahan. Kontras dengan konglomerat
yang dapat menguasai jutaan hektare lahan, namun abai terhadap dampak negatif
penguasaan lahan tersebut bagi lingkungan sekitar. Akhirnya, tinggallah rakyat
yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang kasusnya bertambah setiap
tahun.
Perselingkuhan pengusaha dengan penguasa bahkan semakin
memperparah kerusakan lingkungan. Melalui skema investasi, kapitalisasi lahan
kian sempurna. Dengan dalih ketahanan pangan, mega proyek food estate yang sejatinya adalah proyek bersama
penguasa dan konglomerat lahan pun berjalan mulus. Berdalih pembangunan melalui
skema investasi, lingkungan dirusak, hak rakyat pun dirampas korporasi.
Berbagai kerusakan yang menimpa negeri seharusnya
membuat kita merengung dan menyadari bahwa ada yang salah dalam tata kelola
negeri ini. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus. Manusia-manusia rakus
ini semakin banyak lahir dalam sistem kapitalisme yang segala sesuatunya
berstandar manfaat. Sehingga halal haram hantam. Nasib rakyat jadi prioritas
kesekian.
Sudah saatnya negeri ini diatur oleh sistem yang lebih
baik. Sistem yang tidak menzolimi manusia, dan tidak berpeluang merusak
lingkungan. Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, yaitu sistem
Islam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan
menaungi.
Wallahu’alam bi shawab…
*Penulis adalahAnggota Komunitas Tinta Peradaban Ketapang