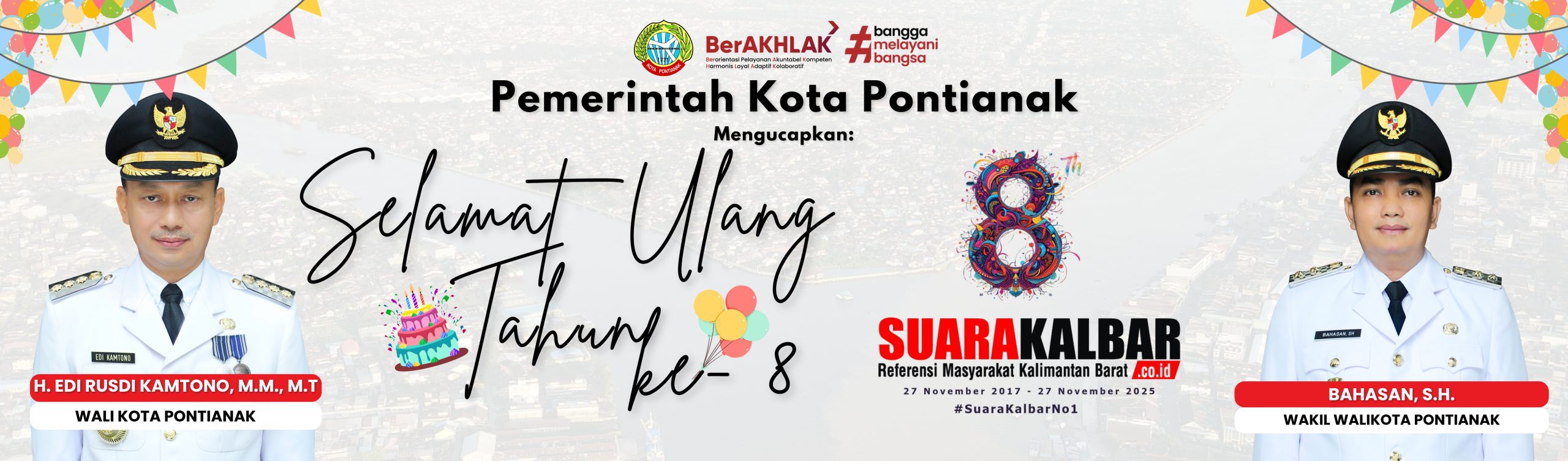Terminal Kijing: Refleksi atas Prestise Global dan Realitas Lokal
Oleh: Agustin Pratiwi
Ketika sorotan kamera menatap megahnya Terminal Kijing di Mempawah, ada cerita lain yang tak kalah penting: suara nelayan kecil yang meredup di balik gemuruh mesin dan narasi kemajuan. Pelabuhan ini memang diposisikan sebagai simpul logistik strategis di barat Indonesia. Dermaga hampir dua kilometer dengan kedalaman 15 meter, kemampuan melayani kapal hingga 100.000 DWT, serta lokasinya di jalur ALKI I menuju Selat Malaka, semuanya membuat Kijing tampak seperti jawaban atas mimpi Poros Maritim Dunia (wartapontianak.pikiran-rakyatcom 12/8/2025). Bersamaan dengan itu, kawasan industri di sekitarnya dirancang untuk mendorong hilirisasi: pabrik sawit, kilang, dan fasilitas ekspor-impor yang diharapkan menambah penerimaan negara, memperkuat daya saing, dan membuka lapangan kerja (antaranews.com). Ya, di atas kertas, jalannya terlihat mulus.
Di lapangan, gambarannya lebih rumit. Nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit kehilangan sebagian ruang tangkap dan akses ke laut yang selama puluhan tahun menjadi nafas hidup mereka. Ekosistem pesisir terganggu, dimana sebagian keluarga terpaksa mengurangi melaut atau berpindah mata pencaharian tanpa kepastian. Pada saat yang sama, ekspansi industri berbasis sawit, bauksit, dan alumina juga sangat berisiko mempercepat deforestasi, mencemari perairan, dan merusak pesisir, problem lingkungan yang sering tak tercatat dalam neraca pembangunan (mongabay.co.id).
Ironisnya, sementara jargon efisiensi logistik digaungkan, data ketenagakerjaan justru menunjukkan ‘badai’ serius: pada Januari–Juni 2025 Kalimantan Barat mencatat PHK tertinggi di wilayah Kalimantan (1.869 kasus), dan pengangguran terbuka pada Februari 2025 mencapai 182.000 orang (pontianakpost.jawapost.com). Disamping itu, harga kebutuhan pokok tetap tinggi, pekerjaan layak terbatas, dan jurang kesenjangan terus melebar. Dengan kata lain, manfaat ekonomi makro belum otomatis ‘menetes’ ke rumah-rumah penduduk di garis pantai.
Jika ditelisik, sumber masalah utamanya bukanlah semata perkara teknis, tetapi menyentuh cara pandang pembangunan dalam sistem yang diterapkan saat ini, sistem kapitalisme sekuler. Dalam pandangan kapitalisme, infrastruktur dibangun untuk memikat investasi dan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Aset publik dibuka selebar-lebarnya namun pembiayaannya sering kali ditopang degan utang atau skema investasi asing yang sejatinya mengikat kemandirian negeri.
Akibatnya, negara rawan kehilangan kendali atas aset strategis jika arus kas seret, sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka, ketika Pelabuhan Hambantota akhirnya jatuh ke tangan asing karena gagal bayar utang. Di hilir, tata kelola yang condong pada oligarki membuat keuntungan terkonsentrasi hanya di segelintir pemain modal saja, rakyat kebanyakan hanya menjadi pengguna berbayar atau malah menjadi pihak yang tergusur. Ketika risiko sosial-lingkungan diabaikan, proyek yang semula dimaksudkan untuk “menciptakan nilai tambah” justru hanya memberikan beban pada komunitas lokal dan ekosistem setempat.
Islam menawarkan koreksi dari aspek hulu: mengubah orientasi, struktur kepemilikan, pembiayaan, dan tata kelola dalam hal ini. Pertama, terkait orientasi. Pembangunan dalam prespektif Islam diposisikan sebagai amanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (maslahah ‘ammah), bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka ekonomi. Indikator utamanya ialah: keterjangkauan kebutuhan pokok oleh seluruh lapisan masyarakat, kelayakan kerja, dan keberlanjutan lingkungan yang ‘sehat’, bukan hanya throughput kargo atau nilai ekspor semata. Kedua, menyoal struktur kepemilikan. Sumber daya strategis, seperti laut, hutan, dan tambang dikategorikan sebagai milik umum (mâl ‘âm) yang tidak boleh diprivatisasi oleh kalangan manapun.
Negara mengelolanya langsung secara mandiri untuk kepentingan rakyat luas; hasilnya masuk ke baitul mal (kas publik), bukan dibagi sebagai laba korporasi. Ketiga, terkait pembiayaan. Infrastruktur publik dibiayai dari baitul mal (pendapatan pengelolaan sumber daya alam milik umum dan pos-pos penerimaan syar‘i), sehingga tidak bergantung pada utang ribawi atau skema yang rentan menggadaikan aset vital maslahah umat. Kontraktor boleh dilibatkan untuk membangun, tetapi kepemilikan dan kendali tetap dilakukan oleh negara yang kemudian pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan hidup masyarakat. Keempat, menyoal tata kelola. Islam menutup ruang monopoli dan penimbunan (ihtikâr), menetapkan standar layanan dengan tarif wajar (bahkan bisa nol rupiah untuk layanan pokok), serta memastikan distribusi manfaatnya sampai ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Jika mekanisme Islam diturunkan pada kasus pengelolaan pelabuhan seperti Kijing, maka yang pertama ditekankan adalah penjagaan pribadi para penguasa agar pelaksanaan tugas senantiasa dilandasi ketakwaan serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperkuat dengan adanya aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar di tengah masyarakat, yang memastikan amanah kekuasaan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, sistem Islam juga menghadirkan sanksi tegas terhadap penyelewengan, sehingga tercipta tata kelola yang bersih, berkeadilan, dan berpihak pada kemaslahatan publik. Dengan pondasi ini, aturan teknis yang diterapkan bukan sekadar administratif, melainkan juga bernilai ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab sosial.
Secara konkret, mekanisme ini mencakup perencanaan berbasis hak dan daya dukung lingkungan, di mana negara wajib memetakan zona tangkap tradisional, jalur biota, serta kawasan pesisir sebelum merancang dermaga, alur pelayaran, atau kawasan industri. Hak penghidupan nelayan dijamin melalui penetapan koridor akses, area tangkap bersama, serta program peralihan penghidupan yang nyata, lengkap dengan kompensasi cepat dan layak bila ruang hidup mereka terambil untuk kepentingan umum.
Standar lingkungan yang ketat diterapkan dengan sistem pencegah tumpahan, pengolahan limbah, dan pemantauan independen berkala, sementara pendapatan pelabuhan dialokasikan langsung bagi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perbaikan fasilitas publik termasuk terkait daerah pesisir. Keadilan kerja ditegakkan dengan perekrutan lokal, standar upah layak, serta larangan outsourcing yang merugikan pekerja. Semua itu dikawal transparansi melalui lembaga hisbah yang menindak rente, kolusi, dan penyalahgunaan konsesi, dengan publikasi kontrak dan laporan kinerja agar masyarakat turut mengawasi.
Bila mekanisme dengan kerangka tatanan sistem Islam dijalankan, maka pelabuhan bisa benar-benar berfungsi sebagai sarana pelayanan publik, memperlancar distribusi kebutuhan, memperkuat kedaulatan ekonomi, sekaligus melindungi masyarakat pesisir dan ekosistemnya. Yang mana berarti negara tidak perlu menjual kendali aset untuk mendapatkan modal, karena pendanaan bersumber dari pengelolaan kekayaan milik umum yang hasilnya kembali ke rakyat. Di sisi lain, dunia usaha tetap punya ruang, terutama di sektor manufaktur dan jasa, namun tidak pada kepemilikan oleh segelintir elite atau monopoli atas sumber daya publik yang strategis.
Oleh karenanya, keberhasilan Terminal Kijing atau mega proyek apa pun seharusnya diukur bukan hanya dari grafik throughput dan nilai ekspor, melainkan dari tiga hal yang kasat mata: apakah nelayan bisa terus melaut dengan layak, apakah lingkungan pesisir tetap hidup dengan baik, dan apakah kedaulatan negeri tidak tergadai. Islam menempatkan tiga hal itu sebagai amanah, dimana pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut bukan hanya didepan rakyatnya, tapi juga di hadapan Allah. Wallahua’lambissowab.
*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS